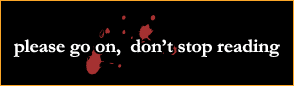
Téyéng merenung, khusyuk sekali. Memang sudah jadi kebiasaannya berlaku seperti itu. Tapi, kali ini terlihat berbeda. Seperti ada sesuatu yang meresahkan pikirannya, entah apa. Mungkin, cuma Tuhan dan dirinya sendiri yang tahu dan paham.
Dia beranjak dari kursi yang sudah menahan beban tubuhnya sekira 10 menit, menuju ke dapur. Dituangkannya air panas ke dalam dua gelas kaca berisi campuran kopi dan sedikit gula itu. Sambil mengaduk berlawanan arah jarum jam, dia melantunkan lagu yang hanya bisa didengar telinganya sendiri.
Terdengar mistis memang, tapi, Téyéng percaya bahwa 'lagu' tersebut bukan sekadar mampu menyelamatkannya dari panas api Jahannam sebab hak prerogatif KekasihNya. Hal-hal remeh seperti mengaduk kopi, diapun ingin melibatkan Beliau SAW. Selama itu bernilai baik, benar, dan indah, Téyéng tak ragu melantunkan, bahkan meneriakkannya sekencang mungkin dengan harapan KekasihNya mendengar. Ya, tentunya dilantunkan setelah mengagungkan namaNya.
“Gimana?” terdengar suara pelan dari tempatnya merenung tadi. “Yaaa, ndak gimana-gimana. Apanya yang mau di-gimana-kan? Memangnya, kalau sudah gimana, tiba-tiba waktu bergerak mundur untuk maju lagi? Nggak, toh?” Téyéng menyahut rumit. Diletakkannya gelas yang masih memunculkan uap-uap kopi panas ke udara itu.
“Kamu memang jancukan, Yéng. Terus, buat apa aku daritadi menanggapi omonganmu yang lebih mirip perempuan PMS (PreMenstrual Syndrome) lagi curhat itu?!” suara itu meninggi seolah dia sedang berorasi melawan kebijakan pemerintah. Walaupun berteriak juga belum tentu akan didengar oleh kacung rakyat yang lagaknya seperti bos itu. Téyéng tertawa lepas, matanya berkaca-kaca.
“Gini, lho, Bon. Aku tadi bercerita itu, tidak hendak melakukan apa dan bagaimana. Cerita, ya, hanya cerita. Jangan mau ditipu pikiranmu sendiri kalau ceritaku memiliki maksud tertentu. Lantas, kalau aku memang curhat, apa, ya, kamu harus tahu langkah-langkahku selanjutnya? Boncu, Boncu. Seorang pendekar tidak akan pamer jurus rahasia! Gitu aja, kamu... ndak... paham?” Téyéng beretorika.
“Terus terang, kalau saja kamu bukan kamu, Yéng, sudah kuhajar sekarang ini,” Boncu nyeruput kopinya. “Apa maksudnya 'kamu bukan kamu'? Cecunguk sok nyufi!” umpat Téyéng. Tawanya menggema.
Mungkin inilah penyatuan. 'Tak ada' adab, moral, apalagi hukum. Makian dan umpatan tidak bisa dinilai sebagai kenegatifan. Bisa jadi itu adalah wujud Cinta dan kemesraan. Téyéng adalah Boncu, Boncu adalah Téyéng. Kepribadianmu, ya, kepribadianku. Milikmu, ya, milikku. Dua orang ini sudah menyatu dalam asumsi masing-masing. Asal jangan poliandri saja.
Sebenarnya kejadian yang menimpa Téyeng itu remeh, sangat amat remeh. Bahkan jauh lebih remeh dari jatuhnya daun yang menguning sebab hembusan angin. Karena pada daun jatuh itu ada sunnatullah. Sedang dalam kasus Téyéng, hanya ada diri dan pikirannya sendiri. Cuma, ini menyangkut martabatnya. Téyéng, yang mengaku sebagai bagian dari orang-orang yang menjunjung tinggi nilai kemartabatan, tidak bisa diam begitu saja jika martabatnya sudah disenggol, apalagi dicekal.
Martabat? Dicekal? Kok, bisa? Bisa saja. Martabat itu abstrak, ghoib. Orang bule bilang, virtual. Seperti ruh yang menempati wadagnya. Ia bisa disematkan pada apa dan siapa, tak tentu wujud dan bentuknya. Dalam kasus Téyéng, ia mewujud dalam sebuah karya. Tampak hiperbolis? Silakan beranggapan demikian. Gusti Allah saja memberikan kedaulatan untuk ber-dhon kepadaNya sesuka hatimu. Kalau cuma dhon hiperbolis pada Téyéng, sih, enteng.
Lalu, karya seperti apa hingga memuat sebuah nilai kemartabatan? Ssstt! Jangan bilang siapa-siapa, ya! Cuma ungkapan Cinta, kok, yang berbentuk surat. Iya, surat!
Ndasmu, Yéng! Lha, badokan surat saja, kok, memuat martabat! Setuju sama Boncu, Téyéng memang jancukan!
Sebentar, sebentar. Demi meminimalisir salah paham, ini harus dijelaskan.
Singkatnya, Téyéng itu, memang hiperbolis, terutama menyangkut soal Cinta. Suratnya, memuat 100% cinta kepada sosok yang dicintainya. Jadi, jika suratnya berisikan kalimat-kalimat lebay wal alay, jangan terburu menertawakan, meremehkan, apalagi mencekal. Percayalah, ini cuma soal Cinta!
Pencekalan yang preventif itu lebih bisa dimaklumi. Tentunya, dengan tetap mengedepankan azas demokrasi. Minimal, tabayyun. Diajak diskusi juga boleh, boleh banget malah. Pahami dulu karyanya seperti apa, maksudnya bagaimana, tujuannya ke mana, dan pelbagai dimensi yang ada. Sudah pernah diajarkan sudut, cara, jarak dan resolusi pandang? Terapkan. Tidak lantas dari sekadar membaca, menafsirkan sendiri maknanya, merasa tafsirnya benar, lalu dengan gagah perkasa mencekal. Ada langkah-langkah taktis yang harus dilalui satu-persatu, baru bisa dilakukan pencekalan. Yah, gunakan cara-cara yang lebih 'manusiawi', kira-kira seperti itu.
Meski terlihat bodoh, dan memang benar-benar bodoh, paling tidak Téyéng pernah merasakan sedikit Sinau Kedaulatan dan Tadabburan. Itu yang membuatnya jauh dari ahmaq dan taqlid. Setidaknya ia merasa begitu. Bodoh boleh, ahmaq jangan. Toh, Téyéng masih bisa dan mau untuk diajak bicara baik-baik.
Dan karena Téyéng sebagai pihak yang dicekal, maka—secara logika—ia terlihat sebagai pihak yang bersalah. “Demi Dzat yang ruhku berada dalam genggamanNya, itu sekadar surat Cinta, Bon. Seperti kau mengirim surat Cinta kepada Wina, seperti surat Ibu kepada anaknya, atau rakyat kepada pemerintahnya. Itu cuma surat!” jelas Téyéng.
Boleh jadi niat Téyéng adalah baik, tapi, apa juga mengandung nilai kebenaran dan keindahan? Andaikata karya Téyéng mengandung nilai kebaikan, kebenaran dan keindahan, kenapa harus dicekal? Pun sebaliknya, sebab kebodohan Téyéng sehingga karyanya sama sekali tak memuat tiga nilai tersebut, kenapa Téyéng tak ditunjukkan ash-shiroth al-mustaqim? Paling tidak, tunjukkan letak kesalahan mutlak pada karyanya. Ya, mutlak. Kalau hanya kesalahan relatif, belum tentu orang lain, terutama sosok dalam karya Téyéng, menganggapnya salah. Bukankah yang dilakukan adalah vonis sebelum pengadilan?
Kalau hanya represif, Adolf Hitler, Benito Mussolini, Joseph V. Stalin, Pol Pot, Kim Jong Il, Saddam Hussain, bahkan sampai Soeharto, mereka juga represif.
Logika saja, jika pencekalan karya Téyéng dilakukan tanpa ada tabayyun sebelumnya, di mana letak kedaulatan yang selama ini didengungkan? Karya Téyéng adalah hasil kedaulatan atas tadabbur-nya, kok, tiba-tiba dicekal karena ditakutkan akan menimbulkan masalah. 'Akan' itu ghoib, belum terjadi, apa yang ditakutkan? Atau, yang mencekal adalah seorang waskito hingga bisa meramalkan bahkan menentukan masalah yang 'akan' terjadi ini benar-benar terjadi?
“Apakah itu kesalahan saya? Kenapa kesalahan anggapan orang atas saya, malah ditimpakan kepada saya? 'Kan, saya justru korbannya. Saya, 'kan, sekadar menjalankan apa yang saya yakini untuk saya jalankan.” Boncu mengutip kalimat mbah Markesot.
“Kalimat siapa itu, Bon? Kaya pernah dengar. Atau baca, ya?”
“SiMbah Markesot. Kenapa memangnya?” Boncu menghisap dalam-dalam kretek di tangan kirinya.
“Gathééél! Sok kamu, Bon! Filsuf gagal kaya kamu, berani berani ngutip kalimat beliau.”
“Lho, apa harus jadi filsuf tidak gagal dulu baru boleh ngutip kalimat? Ya, kamu itu yang sok! Kamu sendiri, apa?! Cuma tokoh khayal dal...” Boncu lenyap sebelum kalimatnya selesai.
“Untuk ukuran tokoh yang aku ciptakan dalam pikiranku sendiri, kamu hebat juga, Bon, bisa mengingat kalimat beliau. Apa gara-gara aku suguh...” Téyéngpun lenyap bersamaan dengan gelas kopi, kursi dan teras rumah yang menjadi latar belakang perdebatan mereka.
Penulis Téyéng dan Boncu nyengir. Dua orang itu tak menyangka jika mereka hanya tokoh rekaan dari seseorang entah siapa. Padahal kalimat yang keluar dari mulut masing-masing, seperti bersumber dari dua orang yang berbeda watak dan kepribadiannya.
Setengah detik setelah lenyapnya Téyéng dan Boncu, laptop tempat mencipta dua karakter itu turut lenyap pula bersama penciptanya. Rupa-rupanya, si pencipta sendiri adalah tokoh rekaan dari Sang Maha Pencipta. Ia bahkan tak sanggup menyelesaikan para...
“Walau tak kupunya...
Tapi, kupercaya Cinta itu indah...”
Dia beranjak dari kursi yang sudah menahan beban tubuhnya sekira 10 menit, menuju ke dapur. Dituangkannya air panas ke dalam dua gelas kaca berisi campuran kopi dan sedikit gula itu. Sambil mengaduk berlawanan arah jarum jam, dia melantunkan lagu yang hanya bisa didengar telinganya sendiri.
Terdengar mistis memang, tapi, Téyéng percaya bahwa 'lagu' tersebut bukan sekadar mampu menyelamatkannya dari panas api Jahannam sebab hak prerogatif KekasihNya. Hal-hal remeh seperti mengaduk kopi, diapun ingin melibatkan Beliau SAW. Selama itu bernilai baik, benar, dan indah, Téyéng tak ragu melantunkan, bahkan meneriakkannya sekencang mungkin dengan harapan KekasihNya mendengar. Ya, tentunya dilantunkan setelah mengagungkan namaNya.
“Gimana?” terdengar suara pelan dari tempatnya merenung tadi. “Yaaa, ndak gimana-gimana. Apanya yang mau di-gimana-kan? Memangnya, kalau sudah gimana, tiba-tiba waktu bergerak mundur untuk maju lagi? Nggak, toh?” Téyéng menyahut rumit. Diletakkannya gelas yang masih memunculkan uap-uap kopi panas ke udara itu.
“Kamu memang jancukan, Yéng. Terus, buat apa aku daritadi menanggapi omonganmu yang lebih mirip perempuan PMS (PreMenstrual Syndrome) lagi curhat itu?!” suara itu meninggi seolah dia sedang berorasi melawan kebijakan pemerintah. Walaupun berteriak juga belum tentu akan didengar oleh kacung rakyat yang lagaknya seperti bos itu. Téyéng tertawa lepas, matanya berkaca-kaca.
“Gini, lho, Bon. Aku tadi bercerita itu, tidak hendak melakukan apa dan bagaimana. Cerita, ya, hanya cerita. Jangan mau ditipu pikiranmu sendiri kalau ceritaku memiliki maksud tertentu. Lantas, kalau aku memang curhat, apa, ya, kamu harus tahu langkah-langkahku selanjutnya? Boncu, Boncu. Seorang pendekar tidak akan pamer jurus rahasia! Gitu aja, kamu... ndak... paham?” Téyéng beretorika.
“Terus terang, kalau saja kamu bukan kamu, Yéng, sudah kuhajar sekarang ini,” Boncu nyeruput kopinya. “Apa maksudnya 'kamu bukan kamu'? Cecunguk sok nyufi!” umpat Téyéng. Tawanya menggema.
Mungkin inilah penyatuan. 'Tak ada' adab, moral, apalagi hukum. Makian dan umpatan tidak bisa dinilai sebagai kenegatifan. Bisa jadi itu adalah wujud Cinta dan kemesraan. Téyéng adalah Boncu, Boncu adalah Téyéng. Kepribadianmu, ya, kepribadianku. Milikmu, ya, milikku. Dua orang ini sudah menyatu dalam asumsi masing-masing. Asal jangan poliandri saja.
Sebenarnya kejadian yang menimpa Téyeng itu remeh, sangat amat remeh. Bahkan jauh lebih remeh dari jatuhnya daun yang menguning sebab hembusan angin. Karena pada daun jatuh itu ada sunnatullah. Sedang dalam kasus Téyéng, hanya ada diri dan pikirannya sendiri. Cuma, ini menyangkut martabatnya. Téyéng, yang mengaku sebagai bagian dari orang-orang yang menjunjung tinggi nilai kemartabatan, tidak bisa diam begitu saja jika martabatnya sudah disenggol, apalagi dicekal.
Martabat? Dicekal? Kok, bisa? Bisa saja. Martabat itu abstrak, ghoib. Orang bule bilang, virtual. Seperti ruh yang menempati wadagnya. Ia bisa disematkan pada apa dan siapa, tak tentu wujud dan bentuknya. Dalam kasus Téyéng, ia mewujud dalam sebuah karya. Tampak hiperbolis? Silakan beranggapan demikian. Gusti Allah saja memberikan kedaulatan untuk ber-dhon kepadaNya sesuka hatimu. Kalau cuma dhon hiperbolis pada Téyéng, sih, enteng.
Lalu, karya seperti apa hingga memuat sebuah nilai kemartabatan? Ssstt! Jangan bilang siapa-siapa, ya! Cuma ungkapan Cinta, kok, yang berbentuk surat. Iya, surat!
Ndasmu, Yéng! Lha, badokan surat saja, kok, memuat martabat! Setuju sama Boncu, Téyéng memang jancukan!
Sebentar, sebentar. Demi meminimalisir salah paham, ini harus dijelaskan.
Singkatnya, Téyéng itu, memang hiperbolis, terutama menyangkut soal Cinta. Suratnya, memuat 100% cinta kepada sosok yang dicintainya. Jadi, jika suratnya berisikan kalimat-kalimat lebay wal alay, jangan terburu menertawakan, meremehkan, apalagi mencekal. Percayalah, ini cuma soal Cinta!
Pencekalan yang preventif itu lebih bisa dimaklumi. Tentunya, dengan tetap mengedepankan azas demokrasi. Minimal, tabayyun. Diajak diskusi juga boleh, boleh banget malah. Pahami dulu karyanya seperti apa, maksudnya bagaimana, tujuannya ke mana, dan pelbagai dimensi yang ada. Sudah pernah diajarkan sudut, cara, jarak dan resolusi pandang? Terapkan. Tidak lantas dari sekadar membaca, menafsirkan sendiri maknanya, merasa tafsirnya benar, lalu dengan gagah perkasa mencekal. Ada langkah-langkah taktis yang harus dilalui satu-persatu, baru bisa dilakukan pencekalan. Yah, gunakan cara-cara yang lebih 'manusiawi', kira-kira seperti itu.
Meski terlihat bodoh, dan memang benar-benar bodoh, paling tidak Téyéng pernah merasakan sedikit Sinau Kedaulatan dan Tadabburan. Itu yang membuatnya jauh dari ahmaq dan taqlid. Setidaknya ia merasa begitu. Bodoh boleh, ahmaq jangan. Toh, Téyéng masih bisa dan mau untuk diajak bicara baik-baik.
Dan karena Téyéng sebagai pihak yang dicekal, maka—secara logika—ia terlihat sebagai pihak yang bersalah. “Demi Dzat yang ruhku berada dalam genggamanNya, itu sekadar surat Cinta, Bon. Seperti kau mengirim surat Cinta kepada Wina, seperti surat Ibu kepada anaknya, atau rakyat kepada pemerintahnya. Itu cuma surat!” jelas Téyéng.
Boleh jadi niat Téyéng adalah baik, tapi, apa juga mengandung nilai kebenaran dan keindahan? Andaikata karya Téyéng mengandung nilai kebaikan, kebenaran dan keindahan, kenapa harus dicekal? Pun sebaliknya, sebab kebodohan Téyéng sehingga karyanya sama sekali tak memuat tiga nilai tersebut, kenapa Téyéng tak ditunjukkan ash-shiroth al-mustaqim? Paling tidak, tunjukkan letak kesalahan mutlak pada karyanya. Ya, mutlak. Kalau hanya kesalahan relatif, belum tentu orang lain, terutama sosok dalam karya Téyéng, menganggapnya salah. Bukankah yang dilakukan adalah vonis sebelum pengadilan?
Kalau hanya represif, Adolf Hitler, Benito Mussolini, Joseph V. Stalin, Pol Pot, Kim Jong Il, Saddam Hussain, bahkan sampai Soeharto, mereka juga represif.
Logika saja, jika pencekalan karya Téyéng dilakukan tanpa ada tabayyun sebelumnya, di mana letak kedaulatan yang selama ini didengungkan? Karya Téyéng adalah hasil kedaulatan atas tadabbur-nya, kok, tiba-tiba dicekal karena ditakutkan akan menimbulkan masalah. 'Akan' itu ghoib, belum terjadi, apa yang ditakutkan? Atau, yang mencekal adalah seorang waskito hingga bisa meramalkan bahkan menentukan masalah yang 'akan' terjadi ini benar-benar terjadi?
“Apakah itu kesalahan saya? Kenapa kesalahan anggapan orang atas saya, malah ditimpakan kepada saya? 'Kan, saya justru korbannya. Saya, 'kan, sekadar menjalankan apa yang saya yakini untuk saya jalankan.” Boncu mengutip kalimat mbah Markesot.
“Kalimat siapa itu, Bon? Kaya pernah dengar. Atau baca, ya?”
“SiMbah Markesot. Kenapa memangnya?” Boncu menghisap dalam-dalam kretek di tangan kirinya.
“Gathééél! Sok kamu, Bon! Filsuf gagal kaya kamu, berani berani ngutip kalimat beliau.”
“Lho, apa harus jadi filsuf tidak gagal dulu baru boleh ngutip kalimat? Ya, kamu itu yang sok! Kamu sendiri, apa?! Cuma tokoh khayal dal...” Boncu lenyap sebelum kalimatnya selesai.
“Untuk ukuran tokoh yang aku ciptakan dalam pikiranku sendiri, kamu hebat juga, Bon, bisa mengingat kalimat beliau. Apa gara-gara aku suguh...” Téyéngpun lenyap bersamaan dengan gelas kopi, kursi dan teras rumah yang menjadi latar belakang perdebatan mereka.
Penulis Téyéng dan Boncu nyengir. Dua orang itu tak menyangka jika mereka hanya tokoh rekaan dari seseorang entah siapa. Padahal kalimat yang keluar dari mulut masing-masing, seperti bersumber dari dua orang yang berbeda watak dan kepribadiannya.
Setengah detik setelah lenyapnya Téyéng dan Boncu, laptop tempat mencipta dua karakter itu turut lenyap pula bersama penciptanya. Rupa-rupanya, si pencipta sendiri adalah tokoh rekaan dari Sang Maha Pencipta. Ia bahkan tak sanggup menyelesaikan para...
“Walau tak kupunya...
Tapi, kupercaya Cinta itu indah...”
(Letto - Cinta ...Bersabarlah)
Comments