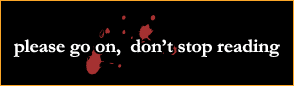
Innalillâhi wa inna ilaihi rôji'ûn.
Mungkin hanya itu yang mampu saya ucapkan saat mendengar kabar berita duka dari kawan-kawan. Adalah ibu Siti Fatma, istri tercinta dari mbah Yai Ahmad Musthofa Bisri, kembali ke HadiratNya sore kemarin. Saya pribadi, belum pernah bertatap muka dengan mbah Mus, pun dengan ibu Fatma. Khalayak lebih mengenal Beliau dengan nama Gus Mus. Seperti lazimnya anak kyai di Jawa, Gus adalah panggilan untuk mereka. Hanya saja, mulut pinjaman saya lebih terbiasa menyebut mbah Mus. Bukan saja karena usia, tapi, lebih disebabkan penghormatan saya terhadap Beliau. Terhadap perilaku, terhadap ilmu Allah yang dititipkan, dan kesemuanya yang mampu Beliau lakukan, sedangkan saya belum.
Perihal kehilangan orang yang kita cintai, bagi setiap orang, hal itu sudah pasti sangat menyakitkan dan sungguh membuat sedih. Sekejap, memori saya terlempar oleh peristiwa berpuluh tahun lalu. Ketika Ayah lebih dulu menghadapNya. Saat itu, saya baru menginjak kelas 5 SD. Karena tak punya figur seorang ayah, saya meminta maaf kepada setiap perempuan yang pernah saya sakiti hatinya. Karena saya belum mampu bersikap layaknya laki-laki.
Untuk ukuran bocah usia 11 tahun, saya belum mengenal bagaimana perasaan sedih sebab ditinggalkan orang yang sangat amat mencintai saya, Ibu dan kakak saya. Hanya tangisan nenek yang membekas di ingatan. Beliau memeluk saya erat, menangis, sembari bertanya entah kepada siapa, “Yo opo kon ngko nek ditinggal bapakmu? Ya Allah..”
Selang bertambahnya usia, lambat laun hati mengajarkan saya tentang kehilangan. Apa saja. Keluarga, barang, kawan, dan, ehem, kekasih (walaupun masuk dalam kategori jelek dan kurang ajar, saya juga pernah mengalami proses jatuh cinta, mencintai dan dicintai). Sempat saya terbersit dalam hati, “Robbi, saya muak merasakan kehilangan,” tapi, tak serta merta ucapan saya mendapat jawabanNya. Dia, 'Azza wa Jalla, lebih memilih saya untuk belajar sendiri dari peristiwa-peristiwa yang Dia tuliskan.
Puncaknya, saya mendengar sendiri dengan telinga dari kepala pinjaman ini. Lantang! Seolah-olah kalimat itu diteriakkan dan ditujukan hanya kepada saya, yang lain ngontrak. Sang Al 'Arif Billah itu mengucap, “hidup itu terserah Allah, semau-maunya Dia. kamu, cukup menjalani. Nggak usah protes!” JEDAR! Seketika itu juga, kabut yang selama ini menutupi hati dan mata saya, hilang sirna. Musnah sama sekali. Sebagai info tambahan, kata jedar di situ tidak ada hubungannya sama sekali dengan Jessica Iskandar. Terima kasih perhatiannya.
Ternyata ikhlas 'semudah itu'. Yah, memang belum sepenuhnya bisa diterapkan dalam setiap hal yang saya alami. Tapi, paling tidak, saya bisa mengatasi beberapa hal klise yang sebenarnya tak perlu membuat saya bersedih, apalagi berduka. Memang terkadang dibutuhkan kesedihan, sebagai tanda bahwa kita—saya terutama—adalah makhluk lemah. Hanya saja, itu bukan satu-satunya cara.
Kita berduka untuk orang-orang yang ditinggalkan, karena mereka harus merasakan lebih lama pahit dan tipu daya kehidupan dunia. Tapi, kita patut bersuka untuk orang yang meninggalkan, karena mereka sudah bersama Sang Maha Ada. Ibu Fatma tak lagi merasakan fana', sedangkan kita? Bersusah payah memantaskan diri untuk sekadar duduk bersama KekasihNya di surga. Masih berusaha untuk mengingat janji yang dilupakan saat dilahirkan ke dunia.
Dunia tak perlu ditangisi, katanya. Lihat mereka, la takhof wa la tahzan, tak takut dan tak pula bersedih. Jika Dia bersamamu, dan kamu bersamaNya, masih bernilaikah sedih dan duka? Daripada mengutuk duka dan kesedihan, maka, sebelum dirimu sendiri yang menghilang, bukankah lebih baik mengajarkan bagaimana menikmati kehilangan?
Selamat berbahagia, Ibu. Gusti Allah dan Rasulullah SAW bersamamu.
Comments